Prohealth.id – Kondisi pengungsi internal di Papua jauh dari standar. Situasi ini sudah sangat kronis sehingga memicu keprihatinan dan kegelisahan.
Keprihatinan dan kegelisahan tersebut kemudian mendorong penelitian atau rapid independent assessment tentang kondisi pengungsian saat ini.
“Mengapa memicu kegelisahan? Karena melihat langkah-langkah negara dalam mengatasi persoalan pengungsi ini jauh dari kata tanggungjawab,” ujar Beka Ulung Hapsara.
Dia menjelaskan, hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan. Beka menyampaikan hal itu dalam peluncuran riset “Pengungsian Internal Adalah Masalah Kronis di Tanah Papua” yang rilis di Jakarta di tengah perjalanan apostolik 12 hari Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik termasuk lawatan ke Indonesia pada 3 – 6 September 2024.
“Hampir tidak ada langkah untuk menyelesaikan persoalan pengungsi ini.”
Komisioner Komnas HAM 2017 – 2022 ini juga menyebutkan martabat manusia yang tak terbatas sembari mengutip dokumen Gereja Katolik “Dignitas Infinita” atau Martabat Manusia.
Dokumen itu menyatakan Gereja diutus untuk menjamin kebebasan dan hak-hak manusia. Martabat manusia yang harusnya mendapatkan penghormatan justru banyak pula yang melanggar.
Ada pelbagai pelanggaran berat atas martabat manusia. Seperti penderitaan para pengungsi, kemiskinan, perang, kekerasan terhadap perempuan, sampai kekerasan digital. Semua tergambar dengan baik dalam “Dignitas Infinita”.
Beka mengatakan pelanggaran itu bukan hanya merendahkan martabat, karena justru menghilangkan martabat kemanusiaan.
Pengungsi-pengungsi menurut Beka, seolah sudah tidak punya martabat lagi. Martabatnya hilang, akibat konflik bersenjata dan abainya negara. Rasa solidaritas kemanusiaan juga mulai menipis. Artinya, saat ini ada ujian terhadap rasa kemanusiaan masa kini.
“Saya mempunyai pengalaman sendiri tahun 2021 akhir ketika masih di Komnas. Saya sempat ke Kisor Maybrat dan melihat sendiri ada perempuan yang waktu itu meninggal. Ada juga anak yang meninggal dalam perjalanan untuk hanya sekadar mencari tempat pengungsian yang aman. Hanya sekadar mencari tempat yang nyaman bagi mereka.”
Temuan Terkait Pengungsi Internal Papua
Data pengungsi internal atau Internally Displaced Person (IDP) yang terkumpul Juli hingga Agustus 2024 dengan metode langsung atau firsthand. Pemilihan responden atau pengambilan sampel berbentuk “snowball sampling” karena keterbatasan akses dan lingkungan keamanan yang tidak memadai.
Pengungsi internal Papua yang mengungsi ke empat wilayah menjadi responden untuk penelitian ini antara lain Nabire di Provinsi Papua Tengah, Wamena di Provinsi Papua Pegunungan, serta Maybrat dan Sorong di Provinsi Papua Barat Daya. Mereka berada di pengungsian secara rata-rata lebih dari tiga tahun.
Hasil penelitian menunjukkan 99 persen pengungsi internal adalah orang asli Papua. Ada empat kebutuhan utama pengungsi internal saat ini. Mayoritas kekurangan makanan ada 97 persen, pelayanan kesehatan 87 persen, dan faktor ekonomi atau mata pencaharian 81 persen, serta tidak dapat sekolah atau pendidikan 90 persen.
“Tidak dapat sekolah itu karena memang ada rasa takut ketika daerah tempat pengungsian mereka itu masih dipantau,” kata peneliti Surya Anta Ginting.
Bantuan datang dari berbagai sumber. Dari pihak gereja, baik Katolik maupun Protestan sebesar 30 persen. Dari sumber keluarga atau kerabat 29 persen, dan atau 24 persen dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sedangkan bantuan pemerintah daerah tercatat masih sangat rendah. Setelah tiga tahun lebih, separuh responden melaporkan tidak menerima bantuan apa pun. Dua pertiga tidak merasa aman dalam situasi saat ini.
Semua responden atau sebesar 100 persen menyebut “konflik bersenjata” sebagai penyebab utama pengungsian. Sebanyak 97 persen responden merasa takut. Sebanyak 41 persen melaporkan merasakan intimidasi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Lalu 39 persen responden mengungkapkan keluarganya mendapatkan ancaman secara langsung.
Responden melaporkan bahwa rata-rata periode pengungsian mereka selama lebih dari tiga tahun meliputi periode antara satu sampai dengan dua tahun pindah-pindah di hutan sambil berjalan kaki.
Mereka menghabiskan 1 hingga 2 tahun dalam perpindahan di hutan dan biasanya berjalan kaki jarak jauh. Sekitar dua pertiga daripada responden terus-menerus berpindah atau tidur di tempat terbuka atau di bawah tenda atau terpal. Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa para pengungsi mempunyai kapasitas sangat besar untuk menanggung trauma secara kumulatif.
“Mereka mengalami trauma dari pengalaman pengungsian ini. Pola pengungsian hampir semuanya sama. Pasca kejadian mereka mengungsi ke gereja atau kalau sudah tidak aman kemudian mereka mengungsi ke hutan. Mereka mengungsi ke hutan pun hanya dengan baju yang melekat di badan,” tutur Surya.
Sambutan Gereja
Konferensi Waligereja Indonesia (WI) menyambut hasil penelitian tersebut. “Penelitian ini sangat berarti bagi kami selain sebagai sebuah data dan fakta. Ini juga menjadi acuan bagi KWI dan Keuskupan di Tanah Papua supaya ke depannya ada program-program atau kemudian uluran tangan yang kongkrit bagi pengungsi,” kata pesan Sekretaris Eksekutif Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Waligereja Indonesia (PSE – KWI) Romo Eko Aldilanto O.Carm.
Persoalan pengungsi ini akan menjadi bagian dari karya pastoral gereja dan mengupayakan terwujudnya rekonsiliasi. KWI juga berharap tim peneliti dapat melakukan lobi dan pendekatan kepada pemerintah untuk segera peduli dan bertindak untuk menangani pengungsi.
Sambutan senada dari Moderator Dewan Gereja Papua (DGP) Pendeta Benny Giay atas hasil penelitian tersebut. Persoalan pengungsi di Papua dalam tujuh tahun terakhir dipicu rentetan insiden yang berhubungan dengan konflik kekerasan. Dia juga menyinggung kebuntuan dalam penyelesaian konflik yang terjadi akibat pendekatan militer yang ditempuh.
“Saya kira itu yang menjadi perhatian kami. Pendekatannya itu pendekatan militer,” ucap Pendeta Benny Giay.
Surya menambahkan bahwa hasil penelitian baru terkait Papua tersebut tidak mematahkan yang sebelumnya. Sebaliknya justru membuat rasa yang baru untuk masuk ke dalam sanubari publik agar publik bisa ikut membuka.
“Bukan sekadar penelitian itu yang membuka. Tetapi publik juga ikut menggugat. Menggugat siapa? Menggugat negara,” jelas dia.
Menurutnya, butuh kolaborasi dengan lembaga sosial lainnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan agar persoalan pengungsi di Papua ini menjadi konsern publik.
“Kita juga bisa ikut menopang tugas-tugas gereja. Saya katakan kepada pengungsi Papua bahwa kamu tidak berjuang sendiri.”
Sedangkan Beka mengungkapkan bahwa dia percaya di Indonesia banyak sekali tokoh dan lembaga kredibel yang sebenarnya mampu untuk menyelesaikan persoalan di Papua. “Saya orang yang sangat optimis terkait itu.”
Dia memandang menyuarakan persoalan di Papua juga merupakan tugas warga negara dan tugas negara adalah menyerap suara itu menjadi kebijakan.
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Manuputty juga sangat mengapresiasi riset masalah pengungsi di Papua tersebut dan akan terus menyuarakannya.
“Kami sangat mengapresiasi riset yang dilakukan ini. Tugas dan panggilan gereja-gereja kami harapkan selalu supaya gereja-gereja di Papua terus-menerus memiliki bukan cuma suara kenabian tetapi juga nyali kenabian,” tutupnya.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

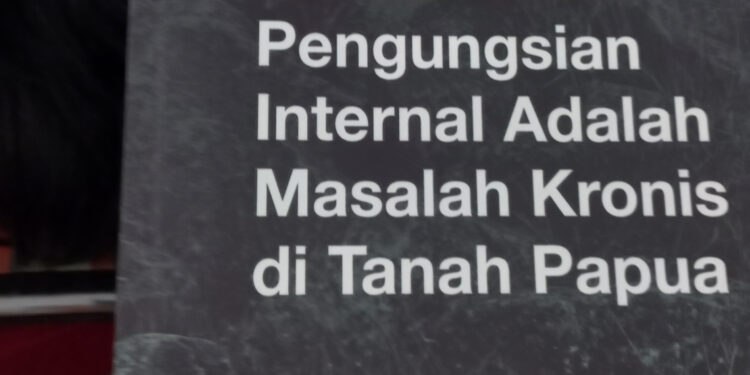
Discussion about this post