Rika, Dewi, dan Iis, tiga perempuan ini adalah orang dengan autoimun (odai). Ada yang telah lama menyandang autoimun dan ada juga yang belum begitu lama. Ketiganya bercerita kepada Prohealth.id, mengenang ketika awal mereka didiagnosis autoimun dan bagaimana menghadapinya.
Protes Berasa Mau “Mati Saat Diberi” Autoimun
“Dua minggu aku bertanya, kenapa aku? Terasa mati itu udah dekat”, kata Rika kepada Prohealth.id baru-baru ini melalui WhatsApp. Ucapannya ini muncul saat ia mengingat kembali masa awal didiagnosis SLE (Systemic Lupus Erythematosus) atau sering disebut lupus, dokter menegakkan diagnosis ini pada Januari 2008 atau 14 tahun lalu.
Tetapi, gejala-gejalanya telah lama ia rasakan. Misalnya, pada saat duduk di bangku SMP, dia tidak tahan terhadap udara panas dan sengatan sinar matahari. Apabila terkena dua hal tersebut, maka ia akan berasa lemas dan pusing. “Waktu itu (SMP) sih nggak sampai pingsan (apabila terkena matahari),” katanya.
Sempat mereda, gejala lupus muncul lagi, salah satunya ditandai Rika yang kerap pingsan. “Ke dokter akhir (tahun) 2007 karena di kelas kuliah sering pingsan. Karena kan dulu kuliah di Surabaya, itu panas banget,” sambungnya. Selepas SMA pada 2003, Rika memutuskan untuk bekerja dulu selama tiga tahun. Uang hasil kerja ini yang kemudian digunakannya untuk biaya kuliah di Surabaya pada tahun 2006.
Dikatakan oleh Rika, dosennya memiliki andil dalam hal ini. “Lalu dosen aku mendorong aku untuk mencoba (periksa) ke (dokter) spesialis penyakit dalam. Gejala waktu itu, selain sering pingsan, muka aku juga sering merah, rambut rontok, kalau drop linu-linu dan cenut-cenut sebadan”, jelasnya detail.
Dokter spesialis penyakit dalam lalu merujuknya ke rematolog yaitu dokter penyakit dalam, subspesialis rematologi. “Diperiksa di sana, langsung disuruh ANA Tes karena dokter (rematolog) udah curiga lupus. Karena katanya udah ada 8 tanda (gejala) yang terlihat dan hasil ANA Tes-ku yaitu langsung dituliskan lupus moderat. Hasil tes keluarnya tahun 2008 bulan Januari”, katanya lagi.
Rika menjelaskan bahwa ada 3 tingkat istilah (untuk kasus lupus) di RS Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, tempat pada saat ia mendapatkan diagnosis lupus. “Ada ringan, moderat, dan satunya lupa, tapi ya artinya lebih parah dari moderat”, paparnya.
Setelah tegak diagnosis lupus, dia wajib rutin berobat 2 minggu sekali ke rematolog tadi. Rika yang saat ini tinggal di Kota Bandung, mengenang ketika pertama kali mendengar kata lupus dari dokternya. Rika yang awam mengatakan awalnya dirinya santai sekaligus takjub karena itu juga pertama kalinya dia seumur-umur mendengar kata lupus dan dari dokternya. “Oh ada ya nama penyakit lupus? (Terus) aku bilang (ke dokter) lupus film itu, dok”, ucapnya heran.
Rematolog yang merawatnya saat itu sempat memberikan satu lembar penjelasan tentang lupus. “Tapi ya normatif aja sih, nggak terlalu ada efek psikologis,” katanya santai. Didorong oleh kondisi fisiknya yang semakin drop dan juga pada saat itu ia tidak memiliki handphone yang bisa digunakan untuk googling mencari infromasi mengenai lupus, dirinya meminta tolong teman satu kost-an untuk googling di warnet segala hal tentang lupus. Hal lain karena dirinya berpikir “perlu” kenal sama si lupus ini.
Dirinya mengakui kena “mental” justru setelah membaca data hasil googling temannya dari warnet. Sebab selain kisah berobatnya, banyak yang menakutkan. Pada titik ini dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, ibarat protes kenapa ia bisa kena, dan sebagainya. “Dua minggu nangis terus. Nggak mau nangis juga ke luar sendiri kok airmatanya. Lagi makan aja tiba-tiba airmata keluar sendiri,” paparnya lirih.
Ia juga menceritakan kepada orang tuanya yang tinggal di Sukabumi. “Tapi mereka (ortu) awam ya. Ya support doa (saja)”, tambahnya. Selama dua minggu tersebut, selain bertanya-tanya, dirinya juga merasa bahwa kematian itu sudah dekat.
“Tapi aku curhat terus sama Allah, salat malam dan tetap sambil baca-baca artikel hasil googling teman,” lanjutnya. Kemudian ia disadarkan. Menurutnya semakin dipikir, memang lupus bisa bikin “mati”, tapi ada juga yang (penyandang) lupus yang bisa sukses hidup (berdampingan) dengan lupus. Dirinya pun memutuskan menjadikan informasi hasil googling itu untuk membikin kuat dan menjadi strategi hidupnya berdampingan bersama lupus.
Serupa tapi tak sama, kisah Dewi juga seperti Rika. Bedanya Dewi menyandang autoimun jenis pemphigus vulgaris (PV), salah satu jenis autoimun yang “menyerang” kulit. “Menyerang membran mukosa dan kulit, biasanya awal pasti manifestinya di mulut kemudian menyebar ke kulit lukanya,” kata Dewi sedikit menjelaskan jenis autoimunnya.
“Aku bingung, asing banget dengernya. Masih santai waktu itu (2015). Terus googling, bingung lagi nemu kata autoimun. Setelah googling kata autoimun, baru deh agak shock karena katanya nggak bisa sembuh,” cerita Dewi kepada Prohealth.id baru-baru ini melalui pesan WA mengenai peristiwa 7 tahun yang lalu
Dewi didiagnosis autoimun jenis PV pada Mei 2015, tetapi sejak 2013 ia telah mengalami gejalanya. Selama setahun itu, setiap hari dia mengalami sariawan yang membuatnya susah makan dan menjadikan tubuhnya kururs kering. Terus mengalami rasa capek yang berkepanjangan. “Kayak habis mendaki gunung, padahal udah tidur dan kerjaan biasa aja”. tuturnya menggambarkan.
Pada September 2014 karena kondisi seperti itu yakni sering sariawan ditambah bibir melepuh sampai hitam, dan menggigil, ia pun dirawat inap di RSUD daerah tempat tinggalnya yakni RSUD Kardinah di daerah Tegal, Jawa Tengah. Akibat belum didiagnosis PV, dokter yang kala itu merawatnya hanya mengatakan dirinya alergi antibiotik saja.
Diagnosis PV baru didapatnya tujuh bulan kemudian dari dokter kulit juga di RS yang sama. Dewi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu alias awam sekali mengenai diagnosis yang diberikan dokter kepadanya saat itu. “Dokter juga tidak jelasin. Cuma waktu itu (dirinya) tanya ke perawat, “ini diagnosis bacanya apa?” Terus dibilang PV”, ingatnya.
Setelah diagnosis itu, Dewi tak langsung memberitahu keluarganya karena dia sendiri masih bingung atau asing dengan jenis penyakitnya tersebut. Ia baru paham setelah mencarinya sendiri melalui internet, juga penjelasan dari dokter lain (dokter pengganti) saat dokter kulit yang merawatnya di RSUD tidak praktek.
Usai didiagnosis PV dan telah memahaminya, Dewi mengatakan ada perasaan denial di dirinya. Ia mengatakan pada awalnya sering menangis karena juga tidak ada yang paham, apalagi PV termasuk jenis autoimun yang langka. “Gimana jelasinnya? Aku aja nyari dari jurnal di luar negeri. Nggak ada artikel tentang PV yang Bahasa Indonesia. Damn!”, ucapnya meluapkan kekesalan.
Ini adalah cerita lalu pada tahun 2015. Kalau sekarang, dia mengaku sudah banyak kasus serupa. Kebetulan saat berselancar di dunia maya, dia menemukan sebuah blog yang dikelola oleh seorang dokter yang juga penyandang autoimun. Lantas Dewi ditawari untuk bergabung dan masih tetap di grup tersebut hingga sekarang. “Nah, karena ketemu yang sependeritaan, agak lega ternyata nggak sendirian. Membantu banget grupnya (grup WA autoimun yang diikutinya itu). Kirain aku mau mati waktu awal-awal, hahaha”, ucapnya lega.
Dewi juga bersyukur bahwa keluarga (orang tua dan saudara kandungnya) mendukung dirinya. Meskipun saat dikasih tahu mereka tidak “mudeng”. “Keluarga shock karena nggak sembuh-sembuh. Terus kalau sariawan parah dan rata semulut. Kata dokter, bukan sariawan tapi luka lepuh. Kayak luka kena knalpot, mlenting terus pecah,” paparnya.
Sedangkan Iis, penyandang autoimun jenis SLE atau lupus tak bercerita begitu banyak kepada Prohealth.id. Iis yang kini berusia 23 tahun dan tinggal di Subang ini didiagnosis SLE pada akhir tahun 2020. Sebelum tegak diagnosis, ia sering mengalami nyeri sekujur tubuh, rambut rontok, dan pada kulit muncul ruam merah-merah.
Didorong oleh kondisi ini, ia pun memeriksakannya ke dokter klinik di pabrik tempatnya bekerja. Oleh dokter tersebut, ia disuruh memeriksakan lebih lanjut di RS. “Saya ke RSUD Subang, dari situ dirujuk ke RS Siloam di Purwakarta,” katanya melalui voice call kepada Prohealth,id. Dokter di RS Siloam Purwakarta-lah yang menegakkan diagnosis SLE kepada Iis.
“Saya malah nggak tahu kalau ini, nggak nyari-nyari tahu juga,” kata Ristiawan Nurhasan saat berbincang melalui pean WA dengan Prohealth.id beberapa waktu ini. Awan, panggilan Ristiawan, mengatakan pada saat dia didiagnosis autoimun, yang terpikirkan hanyalah fokus mencari alternatif berobat, pingin sembuh tanpa harus melakukan suntik obat yang menurutnya tergolong sangat mahal.
Awan (36 tahun) adalah seorang laki-laki penyandang autoimun psoriasis arthritis yakni jenis autoimun yang menyerang kulit dan sendi-sendi tangannya. Sebelum dokter menegakkan diagnosis tersebut, pada kulit kepalanya kerap muncul gangguan. “Kayak ketombe besar-besar gitu, dikletek, nggak lama ada lagi. Terus cepet banget munculnya. Makin digaruk makin melebar luar. Akhirnya ke leher, jidat, belakang kuping sampai perut dan punggung juga,” ujar warga daerah Jakarta Barat ini.
Gejala seperti ini dialaminya selama 2-3 tahun sebelum akhirnya bertemu dengan dokter yang menegakkan diagnosis autoimun kepadanya. Ini ke dokter tersebut sekitar bulan Maret atau April 2018. “Pas di prof baru tahu kalau ini tuh bukan jamur atau ketombe biasa. Semua dilihat sama dia, saya diperiksa. Jari-jari saya yang bengkak dan bengkok saja, awalnya saya nggak tahu kalau itu dari ai (autoimun)-nya. Pas di prof saja (baru) tahunya”, ceritanya.
Tapi Awan hanya sekali berkonsultasi ke prof tersebut lantaran pasca diagnosis, dirinya disarankan untuk suntik obat yang dirasanya mahal sekali. “Sekitar 5 juta sekali suntik dengan prof dan katanya harus rutin sebulan sekali, nggak boleh putus. Saya nyerah makanya nggak balik-balik lagi ke prof”, jelasnya.
Pada satu sisi, dirinya merasa lega karena telah mengetahui penyakit yang dideritanya. “Kalau setelah dengar diagnosis sih waktu itu, jujur biasa saja. Saya teralihkan lebih ke syok sama biaya obat suntiknya waktu itu,” kata Awan sambil membubuhkan emoji tertawa di pesan WA.
Namun dia tak memungkiri ada rasa sedih. Ia menceritakan sehabis dari prof tersebut, dirinya pulang lalu bercerita kepada ibu dan istrinya. Ia bercerita sambil menangis karena kata prof, autoimun belum bisa disembuhkan. Namun ada obatnya yang bisa membantu untuk menenangkan (menstabilkan) penyakitnya (imunnya). Obat yang dirasanya tergolong mahal tadi.
Selain itu, ternyata dirinya juga masih belum bisa menerima kondisi (berstatus penyandang autoimun). Hal ini diceritakannya kepada Prohealth.id dalam wawancara beberapa waktu kemudian. Saat 2018 ia resmi terdiagnosis psoriasis arthritis, Awan hanya menceritakannya ke keluarga sedangkan ke pihak kantor, tidak. Pada saat itu, Awan telah bekerja sebagai marketing di sebuah bank nasional.
“Kantor nggak tahu, saya coba tutupin. Karena malu”, jawabnya saat ditanya mengapa memilih itu. Dirinya juga merasa baik-baik saja, sebelum kemudian autoimunnya flare (kambuh) di tahun 2021. Apakah ada pengaruh sama persepsi laki-laki sakit dianggap lemah? “Nggak mikir gitu sih kalau saya dulu, cuma malu aja kalo orang tahu saya sakit. Gitu aja”, jawabnya.
Pada 2021, dirinya terkena Covid-19 sebanyak dua kali. Pasca Covid-19 yang kedua, autoimunnya kambuh atau disebut flare up sekitar bulan Juni atau Juli 2021. Lalu pada Agustus atau September 2021, dirinya memutuskan kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan rematologi di daerah Tangerang. Inilah pertama kalinya ia kembali kontrol ke dokter. Sebab pasca tegak diagnosis sampai dengan sebelum terkena Covid-19, dirinya menerapkan diet dan dikatakannya cukup memberi progres baik untuk kesehatan diri dan kondisi autoimunnya.
Saat kontrol ke dokter ini, dirinya mengakui kurang cocok dengan terapinya namun sempat dirujuk ke psikolog yang kemudian berdampak signifikan bagi kondisi psikisnya. Psikolog tersebut menyarankan supaya Awan untuk “terbuka” menceritakan kondisi autoimunnya itu kepada kantor atau rekan sejawatnya. Akhirnya keterbukaan Awan kemudian direspon baik dan sampai sekarang. Dia masih terus mengalami pengobatan untuk menstabilkan kondisi autoimunnya.
SLE seperti yang dialami Rika dan Iis, Pemphigus Vulgaris yang dialami Dewi, dan Psoriasis Arthritis yang dialami oleh Awan, semuanya tergolong penyakit autoimun. Pernahkah Anda mendengar autoimun? Penyakit autoimun adalah penyakit yang berkaitan dengan kekebalan atau imunitas tubuh. Dikutip dari alodokter.com, apabila seseorang menyandang penyakit autoimun, maka kekebalan tubuhnya sudah tak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya (error), kekebalan tubuhnya tak lagi memproteksi tubuh penyandangnya dari bakteri, virus, parasit dan sebagainya, yang terjadi justru kekebalan tubuhnya menyerang organ tubuh si penyandangnya.
Ada banyak jenis penyakit yang tergolong autoimun, selain empat yang telah diceritakan di atas. Dalam Medical News Today (medicalnewstoday.com) disebutkan sampai saat ini ada sekitar 100 jenis dan masih ada kemungkinan bertambah karena belum mampu terdeteksi oleh ilmu kedokteran saat ini. Para penyandang autoimun juga didominasi oleh gender perempuan. Laki-laki ada tetapi jumlahnya tak begitu banyak.
Penyakit autoimun ini termasuk penyakit kronis, sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan. Tetapi dengan penanganan yang tepat, bisa dikendalikan. Lantaran yang “diserang” oleh kekebalan tubuh adalah organ bagian dalam (ada juga yang luar seperti kulit tetapi lebih dominan organ dalam tubuh) menjadikan autoimun ini sebagai invisible illness. Penyandang autoimun atau yang biasa disebut Odai (orang dengan autoimun) akan terlihat sehat layaknya orang normal. Seperti Rika, Dewi, Iis, dan Ristiawan (Awan) yang diceritakan di atas.
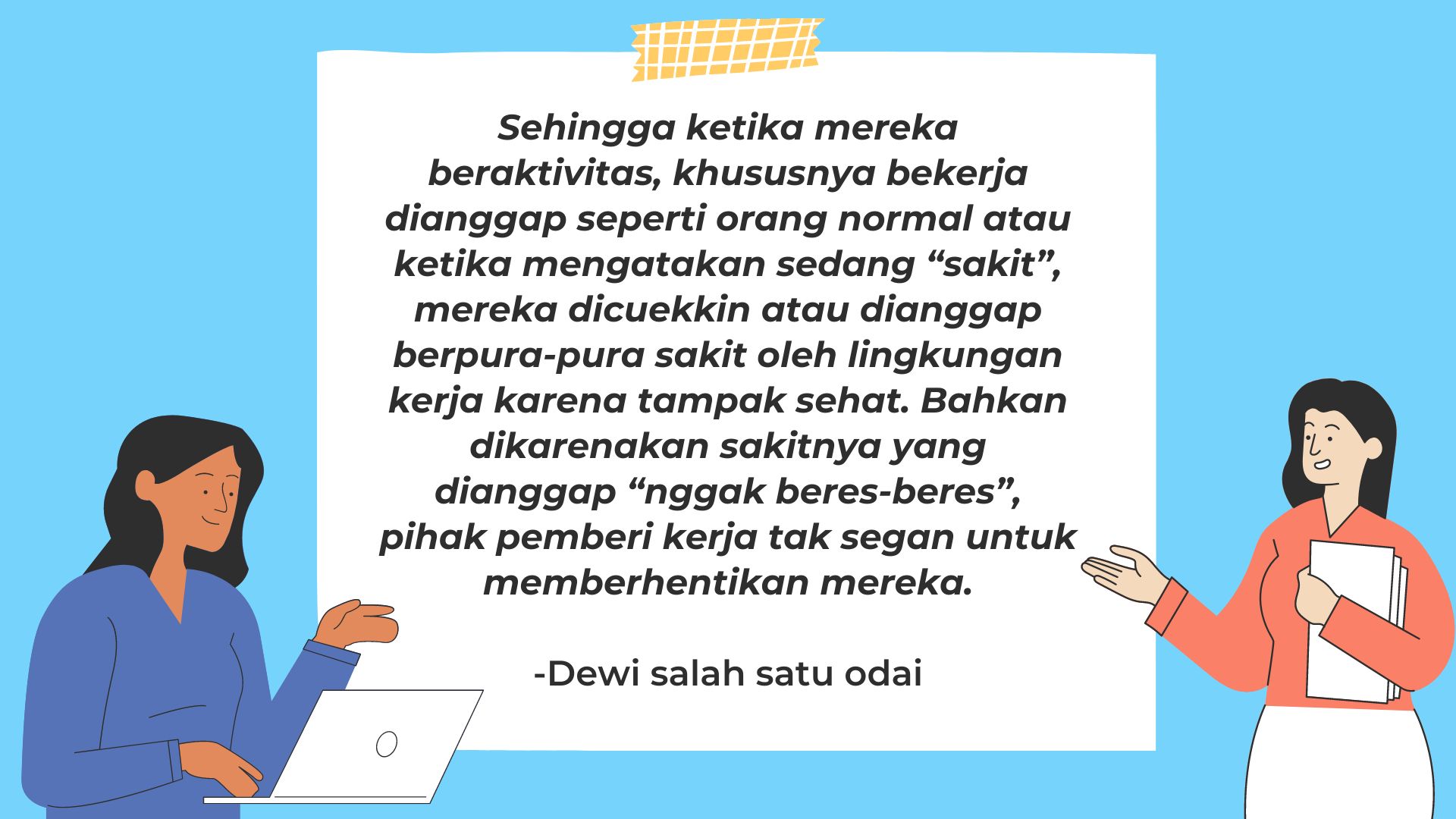
Bekerja untuk berobat dan bertahan
Sebagai penyandang autoimun yang merupakan penyakit kronis. Maka berobat rutin merupakan hal yang wajib. Sebagian nafkah yang mereka dapatkan dari bekerja harus disisihkan untuk biaya berobat. Namun upaya untuk mendapatkan ‘nafkah’ tersebut tak selalu mudah.
Iis saat diwawancara Prohealth.id mengatakan sedang tidak bekerja. Dirinya mengaku telah diberhentikan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Sebelumnya, ia telah bekerja di pabrik sepatu di daerah Subang selama 4 tahun. “Saya baru diberhentikan 3 bulan ini, kak”, katanya dengan pasrah.
Menurut Iis dia tidak diberhentikan secara sepihak. Katanya lagi, sebelum diberhentikan, pihak pabrik memanggil dan membicarakannya dulu soal ini kepadanya. Saat diberhentikan, dirinya juga diberi semacam tunjangan atau pesangon oleh pabrik dan pihak pabrik juga berpesan supaya dirinya fokus berobat dulu.
Ada peraturan di pabrik yang menyatakan bahwa karyawan yang sakitnya lama, bisa diberhentikan. Tetapi ia lupa apakah pertauran ini tertulis atau tidak. Oleh karena itu, dirinya mengerti ketika dipanggil oleh pihak (SDM) pabrik. “Saya waktu itu diajak ngomong dan pasrah saja (bila memang diberhentikan)”, ucapnya. Soalnya ia sadar memang telah sakit-sakitan cukup lama.
Selama dua tahunan pasca diagnosis SLE, ia bekerja sambil menahan sakit. Biasanya nyeri-nyeri di sekujur tubuh yang membuat kerjanya tidak maksimal. Akan tetapi sekarang (pasca diberhentikan) Iis bingung. Lantaran ketiadaan pemasukan maka dirinya tak mampu membayar iuran BPJS setiap bulan.
“Kalau pas bekerja dulu, BPJS kelas 2 dibayarin tempat kerja. Kalau sekarang bayar sendiri (kelas 3)”, katanya. Dia mengaku pasca diberhentikan dan mengalihkan BPJS-nya ke golongan mandiri, sempat membayarkan iuran BPJS mandiri selama satu bulan dan meskipun telah turun kelas yakni ke kelas 3, tetap terasa berat olehnya karena harus membayar iuran setiap bulan untuk 3 orang (Iis, suami dan anaknya).
Selain tidak mampu membayar iuran BPJS setiap bulan, dirinya juga tidak memiliki ongkos untuk melakukan perjalanan ke tempat berobat yakni di RS milik pemerintah daerah Bandung. Kalaupun membeli obat sendiri, dirinya juga tak memiliki dana sebab harga obatnya cukup mahal. Iis bingung dan karena itulah ia memilih menghentikan pengobatan autoimun lupusnya. Walau ia tahu, pilihan yang diambilnya ini dapat membahayakan Kesehatan bahkan nyawanya.
Dewi, yang penyandang autoimun Pemphigus vulgaris atau PV, saat didiagnosis telah berstatus Aparatur Sipil Negara atau ASN di salah satu Pemkab Provinsi Jawa Tengah. Ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. “Iya, setelah cuti sakitnya habis dan udah baikkan, kerja lagi. Tapi ya kan kambuh-kambuhan, awal-awal sering kambuh, kayaknya dua bulan sekali. Sekarang udah mendingan sekitar 2-3 kali kambuhnya”, ia menuturkan.
Kondisi kambuhan yang dirasakan oleh Dewi sebab autoimunnya seperti ngilu sendi, dada sakit, dan sebagainya dan ini dirasakan tak hanya pas awal-awal setelah tegak diagnosis autoimunnya. Sampai bertahun-tahun dan baru mulai berkurang sejak 2018.
Selain berjuang menghadapi kondisi imunnya yang masih “nakal”, di tempat kerjanya itu dirinya juga dihadapkan pada beratnya beban kerja dan rekan kerja atau atasan yang kurang empati. Dewi menceritakan bagaimana kedua hal ini saling berkaitan.
Bekerja di pemkab, Dewi sering mengalami mutasi-mutasi antarbagian. Sewaktu tegak diagnosis PV, dirinya bekerja di bagian hukum Sekretariat daerah (setda). Kemudian pindah ke bagian pembangunan setda, baru ke sekretariat DPRD. Lalu kembali lagi ke bagian hukum setda. “Aku di setwan, berat kerjaanku, akhirnya minta pindah ke HRD (BKD). Balik lagi ke bagian hukum. Ternyata banyak yang mutasi staf-nya, pusing deh”, curhatnya.
Menurutnya di setwan adalah yang paling berat karena sering sekali keluar kota dan harus menghadapi atasan yang arogan. “Udah ngadepin atasan juga harus memfasilitasi kegiatan anggota dewan. Sering banget (aku) sakit”, ceritanya
Padahal atasan “arogan” tadi seorang perempuan dan tahu bahwa Dewi menyandang sakit walau bukan jenis tepatnya yakni Pemphigus vulgaris. “Taunya autoimun. Saking sibuknya, (aku) susah ngatur waktu mau kontrol”, sambungnya.
“Semua pegawai tahu karakter dia”, katanya singkat. Solusinya, Dewi meminta pindah bagian. Pada saat mengajukan permintaan pindah itu, ia melakukannya secara diam-diam. “Aku nggak ngomong ke dia (atasan yang arogan tadi). (Kalau tahu) bisa-bisa nggak boleh (pindah), cuma atasan dia tahu, dan yang lain tahu. Kejadian minta pindah tahun 2020”, jelasnya.
“Aku baru masuk Setwan Januari 2020, bulan Agustus aku sudah sounding ke BKD buat pindah. Udah gak kuat. Tapi bisa pindahnya Mei 2021. Selama 9 bulan lah berjuang biar bisa pindah. Nunggu lama karena harus ada gantinya,” ceritanya getir.
Lebih lanjut diceritakannya bagaimana dirinya bolak balik ke BKD untuk merealisasikan pindah bagian ini. “Tadinya mau Februari 2021 tapi ditahan atasanku (atasan di atas atasanku) maksudnya big boss. Alasanya aku masih dibutuhkan. (Padahal) udah gak karuan tuh badan. Aku minta pindah ya karena saran dokterku. Karena dosis obat gak stabil naik turun terus. Udah nggak sehat katanya lingkungan kerjanya,” jelasnya.
Selain autoimunnya kerap kambuh, bronkitisnya pun kambuh. Menurut dokter spesialis paru yang merawatnya, bronkitis Dewi disebut karena alergi tapi terbukti setelah ia pindah bagian, bronkitisnya tak pernah kambuh. “Kayaknya stres, sampai ke psikiater minta obat biar bisa tenang dan bisa tidur. Terus aku juga sering banget diare dan sakit kepala, hampir tiap hari minum parasetamol” ia menceritakan lagi.
Setelah pindah bagian dan perlahan juga lingkungan kerja Dewi mulai mengerti. Walaupun masih ada juga teman-teman kantor yang tidak mau tahu akan kondisnya.
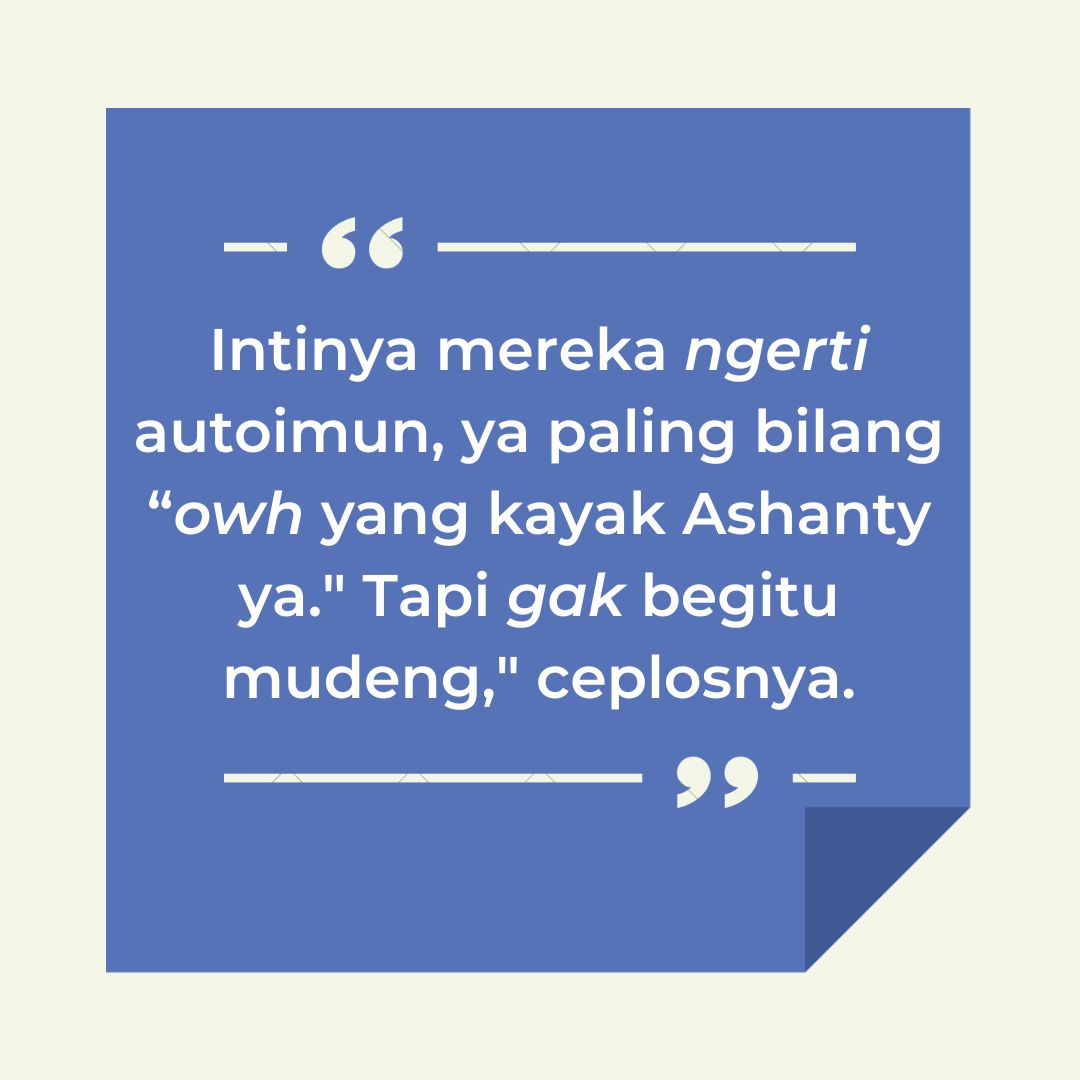
Sedangkan yang tidak mau tahu, salah satunya akan tetap menanyakan hal pekerjaan. “Ya kalo sudah tugas ya harus dilaksanakan, bagian elu ya elu kudu selesai. Biarpun lagi sakit, gak masuk, ya tetep ditanyain kerjaan,” Dewi menceritakannya.
Dewi lantas menyinggung lagi ke beban kerja. Menurutnya ini yang paling mengkhawatirkan. Ia mengatakan ini sambil mengaitkan apada aturan reformasi birokrasi yang sedang digodok untuk selanjutnya diterapkan. “Kayaknya ke depan, beban kerja makin banyak. Aturan makin ribet, nggak cocok sama yang punya sakit kronis, stres. Lebih ke beban kerja. Kan ada reformasi birokrasi tuh. Aturan kepegawaian makin ribet”, ucapnya khawatir.
Dewi mengulang lagi, bahwa semenjak muncul aturan-aturan kepegawaian makin bertambah ribet dari pusat, beban kerja banyak tapi kondisi fisik tidak mendukung dirinya. Terpikir olehnya untuk mengajukan resign dipicu oleh kondisi tersebut namun masih urung dilakukan. “Pengen resign tapi masih butuh duit buat beli obat”, katanya sedih. Selain itu, Dewi juga masih yang menafkahi orangtuanya (ibunya).
Nasib berbeda dalam dunia kerja dialami oleh Rika. Sebagai seorang penyandang autoimun jenis SLE atau lupus, lingkungan kerjanya mendukung kondisi kesehatannya. Rika bekerja di sebuah yayasan sosial yang fokusnya memberikan pembinaan moral dan santunan pendidikan sekolah mulai dari SD sampai dengan SLTA. Lokasi tempat kerjanya di daerah Buah Batu, Kota Bandung.
Telah terhitung 11 tahun dia bekerja di tempat tersebut. “Tahun 2011 masa magang di tempat kerja,” katanya singkat. Rika menuturkan bahwa 6 tahun pertama masa kerjanya (2012-2018) banyak perkerjaannya yang menuntut berhadapan dengan orang dan banyak bicara. Diakui olehnya, perkerjaanya saat itu cukup membuatnya lelah macam-macam, mulai dari sakit kepala, pegel bagian muka dan rahang. Selain itu juga cukup berat baginya untuk menyesuaikan aktivitas pagi saat itu. “Sampai aku ditawarkan kerja part time aja. Jadi mulai kerja siangan”, ungkapnya.
Namun dia menolak dan mencoba mensiasati seperti mulai beristirahat lebih cepat kala malam hari dan paginya walau kurang energi, ia mencoba beraktivitas fisik di luar, seperti piket kebersihan. “Jadi badan kebawa suasana aktif”, sambungnya.
Hanya diakuinya, walau sudah berusaha, tetap saja sebelum jam istirahat kantor yaitu jam 12 dimulai, is sudah mulai kleyengan mengantuk dan capek. Di kantor memang ada jatah jam istirahat selama 1 jam. Namun dirnya mengatakan awal-awalnya sering minta izin beristirahat hingga 2 jam. Mengenai hal ini, ia mengatakan pernah ada SDM junior yang mengomentari “banyak banget tidurnya”.
Ini semua dulu saat belum ada alat komunikasi kantor bersama. Setelah ada alat komunikasi kantor bersama segala izin bisa dijelaskan di sana, tentang apa yang terjadi dan dirasakan. “Izin ke dokter dan surat-surat dokter pun bisa diinfokan di sana (grup WA kantor). Jadi sekalian jelasin sih, kondisiku kek apa. Lama-lama mereka semua mengerti”, paparnya.
Sampai sekarang, diakuinya pasti ada beberapa hari dimana dia izin beristirahat beberapa jam lebih lama dari jam istirahat yang dijatahkan kantor. “Biasanya jelang weekend itu badan kayak udah capek aja, fatigue gitu”, imbuhnya.
Walaupun dalam 4 tahun belakangan ini, jenis pekerjaannya telah bergeser ke lebih banyak depan komputer. Kalaupun masih bertemu orang, tidak terlalu menuntut banyak bicara sehingga dirinya lebih bisa mengatur energi.
“Karena lingkungan udah paham kondisi dan selalu suka amanah yang dikasih. Jadi nggak kepikiran cari kerjaan lain. Dikasih amanah baru, jadi nambah bikin aku belajar hal baru”, katanya menjawab pertanyaan Prohealth.id tentang apa yang membuatnya betah di tempat kerjanya.
Tapi bukan berarti tiada hambatan. Mengenai hambatan tetap ada, seperti dibilang terlambat lalu mudah lupa, nyasar di jalan, tiba-tiba linglung di jalan atau faktor human error kayak men-delete file yang seharusnya disimpan. Juga pernah faktor dari autoimun lupusnya yang tidak bersahabat, yang hingga menyebabkannya harus diopname pada tahun 2014 karena alergi. Rika mengingat kembali pada amanah tadi.
“(Apalagi) sekarang ada 2 orang lainnya, staf di kantor yang kena autoimun dan kalo lagi pada drop, gejalanya mirip-mirip. Nah, jadi tambah ngerti lingkungan (kantor)”, infonya.
Dokter Fiblia, seorang dokter spesialis penyakit dalam mengatakan bahwa odai bisa bekerja termasuk di sektor formal baik pemerintahan (ASN) atau swasta. “Bisa dong! Odai sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan individu sehat, Hanya saja dikarenakan sifat penyakit autoimun, ini biasanya perjalanannya kronik dan bisa up and down keadaannya. (Jadi) odai biasanya mengalami sedikit penurunan kualitas hidup dibanding individu sehat,” terangnya kepada Prohealth.id melalui wawancara WA baru-baru ini.
Konsultan alergi imunologi yang saat ini berpraktek di RS Haji Adam Malik, Sumatra Utara ini mengatakan lantaran kronis itu maka odai harus minum obat rutin dan harus menggunakannya dalam jagka waktu yang lama. Akan tetapi sekali lagi ia menekankan bahwa obat-obatan yang diminum untuk terapi penyakit autoimun tidak akan banyak mengganggu kualitas hidup odai
Menurutnya, obat (untuk) odai hanya perlu diminum dan biasanya (dengan dosis) paling banyak dua kali dalam sehari, dan tidak ada efek sampingnya yang dapat mengganggu aktivitas dalam bekerja. “Karena efek samping (obat-obatan) odai biasanya terjadi dalam waktu yang lama, hal ini pun (efek samping) akan terjadi jika odai tidak patuh (minum obat) dan tidak rajin kontrol,)” jelasnya.
Namun, dokter Fiblia memberikan beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh para odai yang bekerja. Tak sebatas obat yang menjadi perhatian. Termasuk juga lingkungan, zat kimia, dan psikis (stres). Untuk faktor lingkungan, paparan sinar matahari jika odai bekerja di luar ruangan wajib diperhatikan. Hal ini mengingat sinar Ultraviolet (UV) matahari dapat mengaktifkan sistem imun sehingga aktivitas penyakitnya dapat meningkat. Penyandang autoimun jenis lupus biasanya tidak bisa terkena paparan sinar matahari. “Maka hal ini seharusnya disikapi dengan menghindari paparan sinar matahari, bisa dengan menggunakan pakaian yang melindungi (menutupi seluruh) tubuh seperti topi, jilbab, lengan panjang, celana panjang, pakai sunblock biasanya SPF 50 atau pakai payung,” infonya.
Kalau untuk zat kimia, ini juga dapat mencetuskan teraktivasinya sistem imun. Beberapa zat kimia itu misalnya merkuri, pestisida, aluminium, asbes, trichlorethilen, dan lain-lain. Sedangkan faktor stres di lingkungan kerja, dapat menyebabkan aktivitas penyakit autoimun menjadi meningkat.
Terkait ini, ia menekankan pentingnya odai memiliki partner (caregiver) yang bisa menerimanya dengan baik sehingga odai merasa lebih nyaman dan menjadi tidak banyak mengeluh. Hanya dikatakannya lagi, itu sulit (memiliki rekan yang bisa memahami). “Seharusnya atasan dan teman sekerja memahami posisi odai,” imbuhnya.
Melihat dari dua sisi
Prohealth.id kemudian mewawancarai psikolog yang juga konsultan HRD, Maria Theresia Widyastuti via zoom beberapa waktu lalu. Menurutnya ada beberapa hal yang menimbulkan stigmanisasi negatif odai di dunia kerja. “Informasi mengenai autoimun masih sedikit di masyarakat, terutama terkait dunia kerja. Jadi pihak pemberi kerja (HRD) belum tentu mengerti sehingga mempengaruhi keputusan HRD karena minim info tadi”, katanya.
Jika dalam posisi seperti ini maka yang bisa dilakukan odai, misalnya saat melamar kerja harus diinformasikan ke HRD mengenai penyakitnya dan menyakinkan bahwa penyakitnya tidak membahayakan orang lain, dan masih dapat menunjukkan kinerja sesuai kebutuhan perusahaan. Terlebih jika ada tes kesehatan sebagai prasyarat seleksi maka pihak-pihak penyeleksi perlu diinformasikan. Menginformasikan ini juga untuk mengedukasi penyakit autoimun tersebut ke masyarakat. Ia mengatakan tidak perlu menunggu pihak-pihak tertentu untuk memulainya. Tetapi dari diri sendirilah (odai tersebut) yang memulainya. “Karena kita kan memperjuangkan nasib kita sendiri,” tegasnya. Makanya sebagai odai dituntut untuk proaktif mengedukasi masyarakat mengenai penyakit autoimun ini.
Maria Theresia Widyastuti atau yang akrab dipanggil Widya sengaja menekankan pentingnya informasi bagi masyarakat tentang autoimun dan odai di tempat kerja. Sebab memang demikian, informasi terkait autoimun yang disebarkan ke masyarakat nantinya juga akan sampai ke pihak HRD secara tak langsung dan ini harus dilakukan secara terus menerus supaya nantinya mereka (masyarakat dan perusahaan) bisa memahami. Hal inilah yang telah dilakukan Dewi sejak beberapa bulan lalu, yang mulai mengedukasi orang-orang di sekitarnya seputar autoimun PV yang diidapnya. “Aku sekarang mulai share-share info autoimun via Facebook kadang story WA. Barangkali dianggap lebay ya bodo amat”, katanya santai.
Widya sendiri kemudian mencontohkan pengalamannya yang mengetahui autoimun Lupus setelah bertemu dengan salah satu penyintasnya. “Saya aja tahu mengenai lupus setelah ketemu dengan Bu Dian Syarief [pendiri Yayasan Syamsi Dhuha di Bandung yang bergiat pada edukasi autoimun lupus], itu pas tahun 2002,” katanya. Dari pertemuan itulah dirinya kemudian mendapat informasi mengenai lupus yang pada saat itu masih terbilang jarang.
Kemudian, masih dilihat dari sisi perusahaan, apabila (pekerja atau calon pekerja) sakit maka identik dengan biaya (cost). “Sudah pasti (perusahaan) nggak mau kan keluar uang untuk orang sakit atau tidak produktif?” tanyanya. Untuk ini, ia mengatakan perlu dijelaskan dari sudut pandang social responsibility. Ia mencontohkan penyandang disabilitas. “Itu (sekarang) sudah ada yang diterima di perusahaan. Harusnya odai juga bisa diterima kerja,” tuturnya.
Lalu kedua, sampai saat ini autoimun belum dijadikan perhatian oleh pemerintah. Ia mencontohkan penanganan autoimun menggunakan BPJS yang masih belum jelas dimana standarnya berbeda-beda antara satu RS dengan RS lainnya. Terkait ini, Prohealth.id telah menghubungi Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI guna menanyakan data-data semisal jumlah penyandang autoimun di Indonesia, dan lain-lain. Namun sampai dengan liputan ini selesai ditulis, data tersebut belum ada.
Di Indonesia, penyakit autoimun sendiri tidaklah termasuk sebagai salah satu prioritas dalam penanganan penyakit tidak menular (PTM) dalam skema BPJS. Informasi ini diungkapkan oleh Eva Susanti, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes RI saat webinar daring dalam rangka memperingati Hari Arhtritis Sedunia pada Minggu, 30 Oktober 2022. Penyakit-penyakit tidak menular yang pada saat ini termasuk prioritas pemerintah semisal hipertensi, obesitas, diabetes melitus (DM), stroke, dan kanker. Sedangkan pembiayaan kesehatan terbesar PTM berturut-turut untuk penyakit kardiovaskuler, kanker, stroke, dan gagal ginjal kronis.
Dikatakan oleh Eva, pada saat ini pihaknya fokus pada 4 PTM ini dulu. “Buka karena tidak perhatian, tapi karena keterbatasan pembiayaan dari APBN,” tuturnya.
Mencari solusi bersama
Widya menilai hal odai yang belum menjadi perhatian oleh pemerintah, apalagi perlindungan tenaga kerja belum jelas yang mengatur tentang penyakit kronis atau UU tenaga kerja yang spesifik mengaturnya. Apa yang dikatakan oleh Widya ini, dibenarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) melalui Kepala Pemberitaan dan Media Kemenaker, Andri Himawan. Andi mengatakan bahwa belum ada UU yang mengatur secara khusus perihal pekerja penyandang penyakit kronis (autoimun) tetapi kalau disabilitas ada. “Kami adanya aturan khusus bagi pekerja disabilitas, mbak. Secara khusus tidak ada aturan pekerja dengan penyakit kronis (autoimun)”, jawab Andri melalui pesan WA kepada Prohealth.id (21/10/2022).
Apakah memang perlu dibuat UU Ketenagakerjaan yang khusus untuk pekerja penyandang autoimun? Odie Hudiyanto, selaku Praktisi Hukum Ketenagakerjaan mengatakan bahwa hal tersebut sudah dijamin oleh UU. “Tinggal pelaksanaannya diawasi oleh pemerhati hukum ketenagakerjaan”, katanya melalui pesan WA.
Odie yang biasa memberikan training seputar isu ketenagakerjaan menyatakan bahwa prinsipnya seorang pekerja tidak bisa di-PHK dengan alasan sakit. “Apalagi penyakit autoimun bukan penyakit menular,” infonya.
Kemudian ia melanjutkan, bahwa perlindungan pekerja atas ancaman PHK oleh pihak pemberi kerja diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 81 No 40 sebagai perubahan UU Ketenagakerjaan No 13/2003 yang isinya pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit tidak melampaui 12 bulan. Namun jika sudah melebihi 12 bulan, pemberi kerja dapat melakukan PHK dengan memberikan kompensasi sebesar 2 PMTK (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) atau 2 kali ketentuan Pasal 40 UU Cipta Kerja.
“Ingat ya. Sakit secara terus menerus. Bukan sakit yang on-off,’ tegasnya.
Tetapi apakah itu cukup? Di sini, Widya menilai perlu adanya support system. “Ini perlu sekali,” katanya. Support system di sini karena adanya kesadaran bahwa edukasi mengenai autoimun di masyarakat dan dunia kerja masih minim. Ia menjelaskan, support system merupakan dukungan orang-orang seperti teman, sahabat, atau keluarga yang dipercaya dan dapat membantu penderita melewati masa-masa sulit secara sistematis. Maka orang-orang dalam support system ini pun mendapat edukasi yang tepat untuk mendukung dan membantu para penderita sakit.
Support system, lanjut Widya, harus diawali dengan kejelasan informasi sehingga terbentuk dukungan untuk penderita. “Dengan adanya support system ini, maka akan membantu penderita merasa nyaman, mengurangi stres, membantu mengambil keputusan, meningkatkan motivasi, hingga menjadi pribadi tangguh yang dapat bersahabat dengan penyakit yang dideritanya dan melewati semua proses sakitnya, paparnya. Konsep support system dari Widya ini serupa dengan yang dikatakan oleh (sebelumnya) dokter Fiblia bahwa penting bagi odai untuk memiliki partner (caregiver) yang bisa menerimanya dengan baik sehingga odai yang bersangkutan merasa nyaman dan tidak banyak mengeluh (terkait kondisinya. Hanya (mengulang kembali perkataan) oleh dokter Fiblia, bahwa agak sulit untuk memiliki partner yang bisa memahami tadi.
Antara harapan dan kenyataan
Meskipun telah nyaman dengan pekerjaannya, Rika yang bekerja di Yayasan Sosial yang berfokus pada bidang pendidikan dan menyandang autoimun jenis SLE atau lupus mengakui bahwa masih ada harapan-harapan sebagai odai yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dikatakannya, sebenarnya kantornya sudah memberi banyak kelonggaran kepada dirinya. Semisal diperbolehkan izin istirahat di sela-sela pekerjaan “Asal pengumuman dulu, soalnya aku banyak dicari, orang pada butuh,” terangnya.
Namun namanya juga manusia, pasti ada (harapan). Tetapi ia mengatakan harapannya sebagai harapan yang kecil-kecil sih. “Ingin gitu ruangan kerja yang jauh dari bisisng mesin-mesin. Soalnya bikin pusing kepala,” harapannya ini terkait dengan kondisi kesehatannya.
Lalu terkait cuti, ia ingin bisa menikmati jatah cutinya secara full. Rika menceritakan jika ia memiliki jatah cuti sebanyak 12 hari dalam setahun. Tapi karena didorong oleh tanggung jawab moral dan psikologis (posisinya penting di tempat kerja) maka ia sering tidak full mengambil cuti. “(Sebab) terdorong untuk kembali ke kantor kalau urusan pribadi udah beres. Nggak disuruh sih. Tapi kayak dorongan karena orang-orang perlu ke aku,” jelasnya.
Sedangkan Dewi yang berstatus ASN dan memiliki autoimun jenis PV (Pemphigus Vulgaris) berharap adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai dispensasi untuk pekerja yang punya sakit kronis. “(karena sepengetahuanku) belum ada regulasi yang mengatur tentang dispensasi pekerja yang punya sakit kronis baik di swasta atau negeri karena ya gitu deh, pemerintah dan yang bikin aturan nggak aware sama kita yang sakit kronis”, katanya.
Menurutnya, yang ada malah mungkin pemilik sakit kronisnya yang disuruh keluar kerja (resign) karena dianggap sudah tidak kompeten. “Nggak capable”, tegasnya.
Dewi pun mengulang sekali lagi bahwa sebaiknya sih ada aturannya. Juga terkait jenis tugas pekerjaannya. “Kan bisa tuh disesuaikan jenis pekerjaannya sama sakitnya. Gajinya dikurangi nggak apa-apa sih. Kan fair ya buat yang kerja lebih berat buat yang normal dan yang punya sakit kronis. Yang penting haknya dihargai”, harapnya. Menurut psikolog Widya, usulan yang dikemukakan oleh Dewi ini bisa berdampak baik untuk odai tersebut. “Kalau bidang pekerjaan sesuai, maka akan berdampak positif pada kondisi kesehatannya (odai)”, imbuhnya.
Lanjut kepada Dewi, akan tetapi ia menekankan jenis pekerjaan disesuaikan sama sakitnya dengan syarat selama penyandang penyakit kronis tersebut (autoimun) masih bisa bekerja. “Selama masih bisa bekerja lho ya”, tuturnya menutup wawancara dengan Prohealth.id.
(Tulisan ini adalah hasil fellowship ‘Mengubah Narasi Gender di Media Massa yang diselenggarakan oleh Magdalene.co dan Kabar Sejuk)
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi


Discussion about this post