Farid masih ingat betul bagaimana dukungan ibunya ketika dia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Ya, Farid adalah penyintas Tuberkulosis (TBC). Dia menceritakan bagaimana sang ibu selalu mendukungnya.
“Tetap tidak bakal meninggalkan saya. Itu yang membuat saya bersemangat. Istilahnya ada yang menantikan saya untuk sembuh. Ternyata ada yang masih perhatian dengan saya,” ujar dia.
Farid tak bisa lupa bagaimana tertular penyakit yang mengubah hidupnya ini. Saat masih bekerja di sebuah kapal niaga beberapa tahun lalu, ada seorang rekan kerjanya yang mengalami batuk. COVID-19 baru melanda dunia waktu itu dan memakai masker belum menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari.
Tak lama berselang, Farid pun merasakan gejala yang sama. Mengalami batuk, demam dan berkeringat pada malam hari meski pendingin ruangan nyalakan. Dia pun kemudian memeriksakan diri di sebuah rumah sakit di Jakarta. Hasil diagnosa menyebut ia mengalami COVID-19 sehingga sempat melalui proses karantina.
Namun pasca beberapa pemeriksaan, penyakitnya bukan COVID-19. Seorang kerabatnya lalu menyarankan Farid untuk rontgen. Hasilnya, nampak flek di paru-paru. Dia pun melanjutkan pemeriksaan sehingga terdeteksi ia menderita TBC.
Diagnosa ini membuat kehidupan Farid berubah 180 derajat. Sejumlah rencana yang dia susun usai lulus sekolah pelayaran pun tak bisa terlaksana. Seperti membangun bisnis dan membeli rumah untuk keluarganya.
Tak hanya harapan yang pupus, dia pun mengalami stigma dan diskriminasi. Perusahaan memutus kontrak ketika ua sedang menjalani pengobatan. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. “Kalau di pelayaran, selama tidak berlayar ya tidak mendapat upah,” ungkap Farid.
Reaksi orang terdekatnya menambahkan perasaan sangat tertekan. “Ayah seperti menyalahkan saya. Istri dan anak menjauhi. Puncaknya saat istri memutuskan untuk berpisah,” jelas dia.
Namun kehadiran sang ibu menjadi sandaran Farid saat badai kehidupan datang bertubi-tubi.
TBC Membuat Kehidupan Kembali Ke Awal
Farid menyebutkan ketika menjalani pengobatan dia sudah tidak bekerja lagi. Butuh waktu sekitar tiga bulan untuk bangkit kembali. “Saya tidak bisa berdiam diri terus dan meratapi nasib,” ucapnya.
Usai tidak bisa berlayar, Farid mencoba mencari pekerjaan lain. “Ini yang membuat bukan hanya berat di badan tetapi berat dari sisi emosional sebenarnya. Saya ingin berkarya di pelayaran tetapi harus tertunda dan mengulang dari awal. Harus beralih pekerjaan.”
Farid mencoba menekuni sejumlah bidang pekerjaan. Dari warung franchise, afiliator travel umroh, hingga otomotif.
Farid pun melalui pengobatan TBC yang berlangsung sampai sembilan bulan. Meski cukup lama, sebenarnya TBC tidak akan menularkan setelah meminum obat secara rutin selama dua bulan.
Sebagai orang dengan TBC, Farid menyadari dirinya merasa beruntung. Karena memiliki “orang baik” di sekitarnya yang memberi arahan dan dukungan. Sayangnya TBC bagi Farid memberi dampak multidimensi. Bukan saja masalah kesehatan tetapi juga mempengaruhi segi ekonomi dan sosialnya.
Mempertanyakan Komitmen
Efek samping pengobatan TBC mengakibatkan seorang pasien tidak bisa bekerja yang kemudian berujung pada pemecatan. Perhimpunan Organisasi Pasien (POP) TB Indonesia membenarkan realitas Farid. Kehilangan pekerjaan tentu sesuatu yang tidak diharapkan.
“TBC harusnya menjadi isu penting secara nasional yang diikuti jaminan perlindungan sosial dan harusnya itu ada,” kata Koordinator Program SR Tematik POP TB Khoirul Anas.
“Indonesia itu punya target eliminasi TBC 2030. Artinya untuk menuju eliminasi itu dibutuhkan sistem yang mendukung. Mulai dari layanan pendampingan, jaminan kesejahteraan sosial, dan seterusnya,” tambahnya.
Khoirul juga menyebutkan TBC menempatkan Indonesia di peringkat dua dunia. Artinya jumlah orang dengan TBC itu di Indonesia sangat besar. Kasus meninggalnya sangat tinggi.
Oleh karena itu butuh perlindungan sosial bagi orang dengan TBC. Efek samping pengobatan dapat membuat orang dengan TBC tidak berobat sehingga berpotensi menularkan ke orang lain.
Namun ide soal perlindungan sosial bagi orang dengan TBC akan sulit terwujud. Pasalnya anggaran untuk pemberantasan TBC masih bergantung pada donor asing.
“Kapan akan memberantas TBC di Indonesia, keluar dari ranking dua, kalau seperti ini? Persentase anggaran juga kecil karena masih didukung oleh donor-donor dari luar negeri,” papar Khoirul.
Sedangkan organisasi masyarakat sipil Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menekankan soal komitmen pemerintah. Meski memandang perhatian pemerintah sudah sangat baik namun penerjemahan dalam bentuk anggaran itu kurang.
“Komitmen pemerintah sudah sangat baik. Indonesia satu-satunya negara yang punya Peraturan Presiden ini di tatanan internasional. Punya Permenaker,” ujar Program Manager Stop TB Partnership Indonesia (STPI) Nurliyanti.
Tetapi peraturan di level nasional tersebut belum memiliki taring yang besar untuk penanggulangan TBC dan belum dapat memberikan perlindungan hukum.
Dia melanjutkan, bahwa ketika membahas komitmen anggaran TBC, anggaran nasional masih sangat terbatas. Padahal TBC itu berdampak multisektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
“Sementara fokus saat ini adalah menemukan kasus dan melakukan pengobatan.”
Nurliyanti menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kebijakan.
“Karena itu kami mendorong keterlibatan semua pihak. Baik itu dari Kementerian Sosial ataupun Kementerian Tenaga Kerja ataupun dinas-dinas lainnya yang tidak berada pada ranah kesehatan. Karena setiap lembaga pemerintahan itu punya peran signifikan dalam upaya penanggulangan TBC,” pungkas Nurliyanti.
Editor: Gloria Fransisca Katharina Lawi

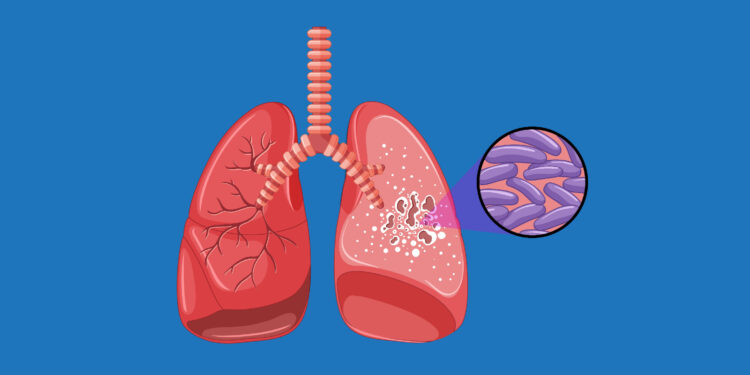
Discussion about this post